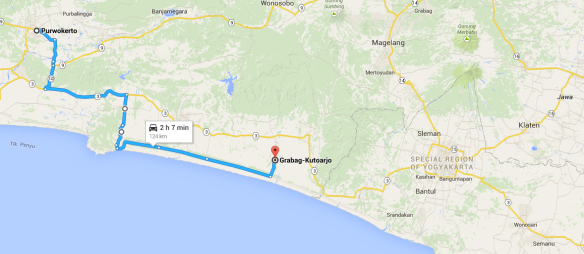“Saya cukup sampai di sini saja. Kalian lanjut saja ke Puncak Pangrango,”
Saya ucapkan kalimat itu kepada rekan-rekan pendakian saya yaitu Yudi dan Sherly ketika kami mulai mendaki ke arah leher Gunung Pangrango, Jawa Barat dari Pos Kandang Badak pada Minggu (3/9/2017) siang. Itulah keputusan yang saya ambil berdasarkan kondisi tubuh yang tak lagi bisa mendukung perjalanan.
Setelah itu, mereka mulai menghilang di tengah rimba hutan Gunung Pangrango dan meninggalkan saya di pinggir jalur pendakian.
Keputusan itu saya ambil bukan tanpa alasan. Langkah saya mulai tertatih-tatih begitu meninggalkan Pos Kandang Badak di area Gunung Gede Pangrango. Kepala saya sudah mulai pusing. Tubuh saya juga terasa gampang lelah. Sementara, nyeri juga menyerang persendian kaki.

Pendaki melewati pos Telaga Biru yang termasuk ke dalam area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, Minggu (3/9/2017).
Sekali lagi, keputusan itu sudah saya ambil dengan matang. Saya sempat berhenti dan menakar kemampuan untuk melanjutkan pendakian Gunung Pangrango. Padahal, saya sempat memutuskan kembali mendaki sejauh 200 meter. Pada akhirnya, saya benar-benar menghentikan pendakian saya dan berputar arah kembali ke Pos Kandang Badak.
Sebelumnya, kami bertiga mengawali pendakian ke Gunung Pangrango pukul 06.30 WIB dari Pos Pendakian Cibodas. Dari perjalanan awal, saya belum merasakan lelah yang berarti. Namun, memang kondisi tubuh saya sedang tidak fit. Saya mengalami sakit flu. Meski begitu, saya tetap bersikeras untuk mendaki gunung yang dahulu merupakan tempat kesukaan aktivis era 60-an, Soe Hok Gie.
Ada kesan seakan memaksakan kehendak atau ego untuk mendaki gunung di tengah kondisi yang tidak fit. Itu jelas tak boleh ditiru. Saya mengakui kecerobohan itu demi sebongkah ketenangan yang ditawarkan oleh Lembah Mandalawangi. Saya pun terkena akibatnya.

Pendaki tengah mendokumentasikan panorama Telaga Biru yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, Minggu (3/9/2017).
Saya dan rekan terlambat sekitar satu jam untuk tiba di Pos Kandang Badak. Idealnya, jika berjalan dengan konstan, Pos Kandang Badak bisa ditempuh dalam kurun waktu tiga jam. Namun, kami menempuhnya dalam waktu empat jam.
Memang berat rasanya harus membuang kesempatan untuk meraih puncak Gunung Pangrango. Apalagi dengan pemandangan bunga edelweis yang menghampar. Dari puncak Pangrango, Gunung Gede bisa terlihat. Gunung Salak juga bisa terlihat dari alun-alun Lembah Mandalawangi.
Semua keindahan itu kini menjadi fatamorgana untuk saya. Saya kini hanya duduk termenung di jalur pendakian Gunung Pangrango sambil mendengarkan alunan angin yang menyapu dedaunan.

Pendaki sedang duduk istirahat di Pos Panyangcangan yang termasuk ke dalam area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, Minggu (3/9/2017).
Keputusan yang saya ambil sudah tepat. Tak baik jika memaksakan kehendak atau menuruti ego untuk mencapai puncak. Walaupun, kali ini suasana Pangrango berbeda dengan kehadiran rekan-rekan pendakian saya, keputusan itu sudah bulat. Saya berhenti di tengah jalur pendakian, meninggalkan rekan-rekan pendakian, dan menunggu kembalinya mereka di Pos Kandang Badak.
Perjalanan menuju puncak Gunung Pangrango via jalur Cibodas juga tak main-main. Untuk menuju puncak Gunung Pangrango di ketinggian 3.019 meter di atas permukaan laut, jalur yang dilalui terbilang ekstrem.
Di jalur menuju Puncak Pangrango, ada kalanya kita harus merayap, melompati batang pohon, memanjat akar pohon, dan melewati jalur tanah yang terjal dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Saya tak bisa menyepelekan meski saya sudah berpuluh-puluh kali berhasil menggapai Puncak Pangrango.
Bisa dibayangkan bila saya tetap nekat melanjutkan pendakian di tengah keadaan yang tak fit. Ancaman bahaya seperti pingsan, hipotermia, dan cedera kaki bisa menimpa saya. Bila akhirnya pun tiba di puncak Pangrango, pastinya akan terlalu sore. Hal itu nanti akan berimbas pada perjalanan turun yang mau tak mau dilakukan pada malam hari. Hal itu jelas sangat berbahaya!
Memang boleh diakui, bisa berdiri di puncak gunung adalah suatu kebanggaan tersendiri. Rasa lelah dibayar dengan keindahan yang ada di puncak gunung. Koleksi swafoto atau foto pemandangan bisa diambil dan lalu diunggah ke media sosial. Kemudian, unggahan foto di media sosial diharapkan bisa menuai respon dari warganet. Cerita-cerita perjalanan juga bisa dibagikan ke teman-teman lain.
Dari semua kebanggaan itu tentu tak mudah untuk dicapai. Ada risiko yang menghadang. setiap saat. Salah mengambil keputusan bisa berakibat fatal. Musibah bisa datang menghampiri setiap saat. Mendaki gunung adalah kegiatan yang penuh dengan marabahaya. Saya menyadari betul bahaya itu.
Pengambilan keputusan yang buruk dikenal sebagai salah satu penyebab musibah. Hal itu termasuk jenis bahaya subyektif (subjective dangerous). Bahaya itu termasuk juga seperti pengetahuan mendaki gunung yang minim, kondisi badan yang tidak fit, dan lain-lain. Di Indonesia, berdasarkan pemantauan saya, bahaya-bahaya tersebut masih banyak menghantui pendaki-pendaki Indonesia.
Dari keadaan yang saya alami, tak seharusnya puncak adalah tujuan pendakian. Pilihan terbaik yaitu berhenti, tak meneruskan pendakian. Tak ada alasan lain untuk melanjutkan pendakian. Keselamatan adalah hal yang utama.

Pendaki sedang berkemah di Pos Kandang Badak yang termasuk ke dalam area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, Minggu (3/9/2017).
Feri, rekan saya di organisasi Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) yang juga merupakan teman dari Yudi sempat berpesan tentang keselamatan sebelum saya pergi mendaki ke Gunung Pangrango.
“Hati-hati di jalan,” kata Feri dalam pesan Whatsapp.
Pesan itu terngiang begitu saya mengalami hambatan itu di tengah pendakian. Pun, perkataan senior-senior saya di Mapala UI. Safety first!
Begitupun dengan orang yang paling saya sayangi, Dea juga selalu mengingatkan untuk hati-hati bila saya akan mendaki. Tak terkecuali pendakian saya hari ini.
Kehatian-hatian memang modal utama dalam mendaki gunung. Setiap pendaki harus bisa mengobservasi keadaan yang ada di sekitar dan yang dialami. Kepekaan adalah hal yang mutlak. Luangkan waktu untuk berpikir. Kata “STOP” merupakan kunci mujarab saat mendaki gunung. Kata punya kepanjangan “Stop, Thinking, Observation, Planning”
Bila menghadapi bahaya, cobalah berhenti sesaat. Jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Pikirkan segala sesuatu kemungkinan yang bisa diambil agar bisa terhindar dari bahaya. Lihatlah keadaan sekeliling kita. Apakah cukup mendukung? Lalu terakhir, susunlah rencana yang paling mungkin untuk menangani bahaya.
Kembali lagi, mendaki gunung tak harus sampai puncak. Mungkin kesimpulan saya itu akan menjadi kontroversial. Apalagi, jika pendaki sudah datang jauh-jauh ke gunung untuk mendaki. Ada biaya yang sudah dikeluarkan, waktu yang sudah diluangkan, dan memilih untuk mendaki gunung. Lalu, apa urusan saya melarang mendaki sampai puncak?
Kredo yang berbunyi, “tujuan mendaki gunung adalah sampai dengan selamat di rumah” itu 100 persen benar tanpa bantahan. Saya belajar bahwa pendakian memang tak harus sampai puncak. Masih banyak kesempatan untuk kembali meraih puncak. Toh, gunung yang akan didaki tak akan pergi.
Bagi saya, pendakian gunung adalah sebuah media untuk menguji seorang pendaki atau individu. Ujiannya adalah bagaimana menyiapkan pendakian, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat sekitar maupun pendaki, kapan batasan fisik bisa menunjang pendakian, dan sederet pertanyaan lain. Bila sudah bisa melampaui ujian itu, maka kita bisa melakukan pendakian dengan baik.
Puncak gunung adalah urusan kesekian dalam mendaki. Keselamatan adalah yang utama. Jangan sia-siakan nyawa demi tiba puncak gunung tanpa pengetahuan yang mumpuni.




 “Mau ke mana lagi nih?”
“Mau ke mana lagi nih?” Saya wartawan, bukan wisatawan.
Saya wartawan, bukan wisatawan. 
 Yang berkembang saat ini, memang pekerjaan “Travel Journalist” ini bak impian semua orang. Itu dari hasil dari pengalaman saya bertemu dengan beberapa orang. Namun, benar memang jarang yang ingin menyelami lebih dalam terkait pekerjaan ini. Istilahnya, hanya tahu tentang jalan-jalan saja.
Yang berkembang saat ini, memang pekerjaan “Travel Journalist” ini bak impian semua orang. Itu dari hasil dari pengalaman saya bertemu dengan beberapa orang. Namun, benar memang jarang yang ingin menyelami lebih dalam terkait pekerjaan ini. Istilahnya, hanya tahu tentang jalan-jalan saja.